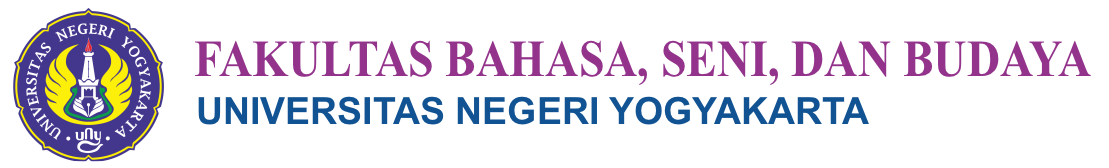Address: Colombo Street No 1, Yogyakarta 55281,
Phone (0274) 550843, (0274) 546719, Fax (0274) 548207
Website: http://fbsb.uny.ac.id
Email: fbsb@uny.ac.id;

ANTROPOLOGI SASTRA JAWA SEBAGAI PEMBUKA JALAN BERPIKIR POSITIF DAN REVOLUSI MENTAL
Assalamu’alaikum, wr.wb.
Salam sastra dan budaya!
Sidang Senat yang khidmat dan mulia.
Yang terhormat Bapak Rektor
Yang terhormat Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan Segenap Anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan Universitas;
Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Negeri Yogyakarta
Yang terhormat Bapak Ibu Pembantu Rektor, para Dekan dan para Wakil Dekan, Direktur dan para Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Biro di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
Yang saya hormati Ibu Ketua dan Anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Yogyakarta.
Yang terhormat pula, para sesepuh, para senior, para dosen, karyawan Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FBS UNY, para mahasiswa, para empu seni dan begawan sastra di DIY dan sekitarnya, serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia.
Puji syukur Alhamdulillahi rabbil’alamin saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, inayah, dan kodrat iradat-Nya, sehingga pada sidang Senat Terbuka yang mulia ini, saya dapat menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar bidang ilmu Antropologi Sastra Jawa, pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga cahaya dan syafaatnya selalu menyinari sang Guru Sejati pada diri kita. Amin.
Hadirin yang saya hormati,
Izinkanlah melalui mimbar yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya ini, saya menyampaikan pidato berjudul: Antropologi Sastra Jawa sebagai Pembuka Jalan Berpikir Positif dan Revolusi Mental. Sebagai pembuka akan saya awali dengan sebuah percikan tembang sinom, dari wulang Dalem Sri Sultan Hamengkubuwana I dalam Serat Laksita Tama yang memuat endapan perintah berpikir positif.
dhuh putraningsun ger sira
iya kulup sun tuturi
aja wani-wani sira
marang sudarmamu kaki
lamun sira njur wani
duraka bakal tinemu
krana wong tuwanira
iku wakiling Hyang Widhi
rumangsaa wit sira tinitah gesang
(Koleksi Museum Sonobuboyo, PBA 236, bahan Macapatan Sonobudoyo, 23 Nopember 2014, alih aksara Ki Parjiono)
Terjemahan bebasnya sebagai berikut.
‘Duh anak saya, jangan berani pada ayah (orang tua) kalian, jika kau berani akan dicap anak durhaka, sebab orang tua itu tidak lain wakil dari Tuhan, maka hidup ini sedapat mungkin mampu merasakan bahwa orang tualah yang menyebabkan kita ada’.
A. Pendahuluan
Hadirin yang saya hormati,
Jika direnungkan menggunakan kacamata antropologi sastra Jawa, tembang sinom di atas, sungguh banyak menawarkan upaya berpikir positif, yang suatu saat dapat menjadi wahana revolusi mental. Berpikir positif menurut Ki Ageng Suryamentaram (1989:11) disebut pangawikan pribadi atau kawruh sejatining gesang. Esensi hidup adalah berpikir. Maksudnya, karena hidup itu tidak statis, bungah-susah, mulur mungkret, itu senantiasa nyakramanggilingan, maka berpikir positif pada Kang Gawe Urip dan sesama justru menjadi jalan untuk perbaikan mental. Revolusi mental adalah penataan ulang, pembersihan diri, dan restorasi harapan hidup. Hal ini dilandasi asumsi bahwa orang yang mampu berpikir positif mentalnya akan bersih sehingga mendapatkan kawruh begja sawetah.
Atas dasar pendapat demikian, dari perspektif antropologi sastra Jawa kita dapat memetik tiga wawasan budaya berpikir positif tembang di atas, yaitu (1) sebagai anak tidak dibenarkan berani kepada orang tua, melainkan harus harus eling, percaya, dan mituhu (berbakti), (2) sebagai anak perlu berpikir positif pada orang tua, dengan cara bersikap bisa rumangsa, bukan rumangsa bisa, (3) petunjuk orang tua, jelas menuju ke arah kebaikan hidup anak. Pemahaman semacam ini seirama dengan gagasan Poyatos (Ratna, 2011:33), antropologi sastra adalah sebuah perspektif interdisiplin yang relatif baru, untuk mengkaji sastra dari aspek budaya. Dalam konteks budaya Jawa, manakala ada anak yang berani durhaka kepada orang tua akan kuwalat, artinya terkena hukum karma seperti jambu mete.
Dalam konteks antropologi sastra Jawa, pantas kita menyelami sugesti Dorson (1972:20-24) bahwa studi antropologi terhadap folklor dan sastra boleh mengungkap aspek keyakinan, mentalitas, dan cara berpikir manusia tentang hidup, melalui lagu, teka-teki, ungkapan dan sebagainya. Saya pun dapat mengamini sugesti ini, sebab melalui implementasi antropologi sastra Jawa ketika saya sedang bingung, buneg, dan galau lalu menghayati ruh tembang tadi ternyata dapat memperoleh pencerahan mental. Pencerahan yang saya rasakan dari larik tembang krana wong tuwanira, iku wakiling Hyang Widhi, ketika taun 2012 simbok saya mengatakan: “Aja wani-wani karo wong tuwa, utamane gurumu, kepiye wae, dheweke sing menehi pepadhang. Najan kowe diidoni bebasane, aja kok wales nganggo idu. Ning becikana Le, sapa ngerti ana niat becik seka wong mau.” Maksudnya, saya dilarang berani pada orang tua, termasuk guru. Jika dimarahi atau diapa-apakan saja, jangan membalas, siapa tahu guru tadi berniat baik.
Mendengar petuah simbok yang diamini bapak dua tahun lalu itu, seolah-olah ada guru sejati yang menuntun batin saya ke nuansa berpikir positif. Dengan berpikir positif ternyata menuntun sampai revolusi mental, yang semula saya sudah ngepel tangan, berubah menjadi lumah tangan yang dalam budaya Jawa disebut kridha lumahing asta. Artinya, apa yang saya lakukan (kridha) senantiasa memohon dengan pasrah (lumahing asta). Ternyata, cita-cita hidup yang sering banyak kerikil tajam, dengan menghayati baris terakhir tembang di atas berbunyi rumangsaa wit sira tinitah gesang dapat tercapai atas ridla-Nya. Kata rumangsa, jika bertumpu pada gagasan Toelken (1979:338) tentang “What can we read out of it?” memiliki kekuatan (the power) batin yang luar biasa.
Dalam perspektif antropologi sastra Jawa, ungkapan bisa rumangsa adalah cara berpikir positif. Antropologi sastra Jawa membolehkan permainan tafsir terhadap karya sastra, sepanjang terkait dengan prilaku manusia. Perspektif semacam ini mengingatkan gagasan Ahimsa-Putra (2003:101) bahwa dalam pandangan sastra antropologi, menulis etnografi itu sama halnya dengan menulis karya sastra. Pandangan ini menguatkan gagasan tentang interelasi sastra dan antropologi sesungguhnya bukan hal yang dicari-cari. Dengan kata lain, perspektif antropologi sastra Jawa adalah ilmu humanistik yang kaya makna. Dengan implementasi interdisiplin antara antropologi, sastra, dan Jawa sebagai identitas lokal, karya sastra dapat dipahami secara mendalam untuk mengungkap perilaku manusia.
B. Antropologi Sastra Jawa Memotret Realitas Manusia
Realitas manusia: (1) gemar berpikir negative, (2) ingin menang sendiri, serba paling, tidak mau diungguli, (3) iri dengki srei, (4) duwe melik (Ki Ageng)
Hadirin yang saya hormati,
Secara ontologi, antropologi sastra Jawa adalah ilmu interdisiplin antara sastra, budaya, dan antropologi. Ilmu ini mencoba mempelajari perilaku manusia melalui karya sastra Jawa. Dari sisi epistemologi, antropologi sastra Jawa merupakan sebuah perpektif mempelajari manusia lewat sastra. Cara yang ditempuh yaitu melalui permainan tafsir budaya terhadap cipta sastra. Biasanya yang menjadi objek kajian antropologi sastra adalah sastra etnografi. Adapun secara aksiologi, antropologi sastra Jawa berguna untuk memotret hidup manusia sebagai fakta estetis. Memotret dalam konteks ini berarti memahami perilaku manusia tentang cara berpikir positif dan revolusi mental orang Jawa.
Sastra adalah kegiatan kreatif, sebuah karya seni (Wellek dan Warren, 1989:3). Upaya mempelajari sastra dari sisi antropologi ini dapat disebut antropologi sastra. Munculnya antropologi sastra, didorong oleh pemikiran Ernst Cassier (1956:44) tentang hakikat manusia sebagai animal symbolicum. Karya sastra adalah ekspresi gagasan tentang hidup manusia melalui berbagai symbol. Gagasan ini, menurut Ratna (2004:353) memunculkan sebuah disiplin baru, yang disebut antropologi sastra, senada dengan istilah psikologi sastra dan sosiologi sastra.
Gagasan antropologi sastra merupakan pengembangan studi sastra dari kacamata antropologi. Hal ini dipertegas lagi dengan pemikiran Paul Benson (1993) dalam bukunya berjudul Anthropology and Literature, dia mencoba mengaitkan antropologi dengan sastra untuk mengungkap kehidupan manusia. Selanjutnya, gagasan baru itu juga menarik perhatian Ahimsa-Putra (2004) dalam bukunya berjudul Strukturalisme Levi-Strauss Mitos dan Karya Sastra. Dia menawarkan kajian struktural terhadap mitos, termasuk folklore, dan karya sastra. Berbagai hal ini sering dimanfaatkan oleh para politikus, untuk meraih suara secara simbolik.
Lewat antropologi sastra Jawa, kita dapat memotret budaya berpikir positif manusia. Berpikir positif dapat menjadi jalan revolusi mental. Berpikir positif adalah tanda orang sehat (waras), sehingga mampu merevolusi mental yang kotor. Berpikir positif oleh para ustad disebut husnudzon (berbaik sangka) kepada Allah azza wa jalla dan sesama manusia, kebalikan dari suudzon (berburuk sangka). Dari sisi antropologi sastra, orang Jawa yang gemar berpikir positif, antara lain dapat tergambar dalam sebuah cerita cekak berjudul Srengenge (Panjebar Semangat, nomer 12, 17 Maret 1990) karya Turiyo Ragilputro berbunyi: “Saben kepethuk uwong mesthi enggal takon, utawa paling ora ngajak mesem.” Kutipan cerita cekak ini, menandai bahwa orang Jawa yang suka berpikir positif akan selalu: (1) sapa aruh, artinya memperhatikan orang lain dengan tegur sapa, tanpa ada beban dan berprasangka buruk sedikitpun, (2) sugih esem, artinya banyak senyum sebagai ibadah, karena senyum manis itu akan menghilangkan sekat-sekat dendam, sebaliknya senyum kecut (esem kecut) sering memunculkan purbasangka yang jelek.
Kisah cerita pendek tersebut jika dipandang dari perspektif antropologi sastra Jawa melukiskan perilaku orang Jawa yang murah senyum dan mahal senyum. Maka ada betulnya jika Keesing (1999:2), seorang antropolog budaya menyatakan bahwa antropologi memberikan pemahaman terhadap manusia. Memahami manusia dapat melalui cipta sastra. Maka interdisipliner antropologi dan sastra menjadi sebuah alternatif untuk melacak pemikiran dan perilaku manusia. Hal ini dapat dihayati melalui kelanjutan kisah cerita pendek Srengenge, bahwa manusia akan diangkat derajatnya apa bila menjalankan tiga laku: “Ana telung perkara. Siji ali, loro ili, telu eling. Ali dumadi seka ali-ali. Tegese, samubarang kang dumadi ing salumahing bumi sakurebing langit ora uwal seka wengkuning surya sejati…Nomer loro ili. Maknane, manungsa mono kudu pasrah, tansah manut ilining tirta sejati. Pasrahna kabeh jiwa ragamu…Sing pungkasan eling. Manungsa urip mono kudu tansah eling, emut marang surya sejati.” Pemikiran cerpenis tentang tiga ajaran keutamaan hidup tersebut adalah bentuk budaya ide. Adapun perilaku adalah perwujudan budaya ide. Antropologi sastra Jawa berupaya meneliti pemikiran dan perilaku manusia lewat tokoh dalam cerpen, yang muncul sebagai budaya dalam karya sastra. Secara etnografis, dari cerpen tersebut tampak bahwa manusia Jawa memiliki tiga pegangan keutamaan hidup.
Sebagai ilmu, antropologi jelas sudah tua umurnya. Antropologi yang bercirikan meneliti bangsa primitif, kini telah berubah. Antropologi pun belakangan tidak hanya mempelajari manusia secara nyata, melainkan juga membaca sastra. Sastra adalah karya tentang sikap dan perilaku manusia secara simbolik. Sastra dan antropologi selalu dekat. Keduanya dapat bersimbiosis, dalam mempelajari manusia lewat ekspresi budaya. Sastra banyak menyajikan fakta-fakta imajinatif. Antropologi yang bergerak dalam fakta imajinatif dapat disebut antropologi sastra. Interdisiplin ini memang tidak dikenal di jurusan antropologi, melainkan mewarnai penelitian di jurusan sastra (Endraswara, 2013:2). Konsep penting antropologi sastra adalah seperti dinyatakan Benson (1993:250) tentang anthropological poetry. Artinya, adalah wawasan antropologis terhadap cipta puisi. Biarpun dia belum menyebut istilah antropologi sastra, dengan istilah antropologi puisi, jelas cukup beralasan kalau ilmu itu dipelajari lewat antropologi sastra. Antropologi sastra tampaknya sebagai pengembangan anthropology experience yang digagas Turner dan Bruner (Benson, 1993:46). Pandangan ini, tampaknya terusik oleh gagasan etnografi fiksi yang berkembang di era posmodernisme. Jagad posmodernisme sastra dan antropologi telah lari jauh ke depan. Sastra tidak hanya sebuah artefak yang penuh estetika, melainkan juga memuat sebuah budaya yang berisi etika. Sastra menawarkan budaya pemikiran dan perilaku manusia dalam hidup sehari-hari.
Yang dimaksud antropologi mengkaji manusia, adalah mempelajari sikap dan perilakunya. Dalam kaitan ini Ki Grangsang Ageng Suryamentaram, di Jalan Barito Jakarta, 13 Januari 2012 dalam acara Junggringan, menyatakan dalam pidato pembukaan bahwa Ki Ageng Suryamentaram pernah berkata: ”Seprana-supréné, aku kok durung tau kepethuk wong,” konon begitulah yang dikatakannya. ”Selama ini, aku belum pernah berjumpa manusia.” Yang dia maksud “wong” adalah orang yang mulia, yang tidak tergiur di antara milik dan melik. Jika hidup masih tergiur dua hal ini, orang akan tamak, mahal senyum, dan banyak berburuk sangka pada orang lain. Hal ini penting, sebab senyum adalah potret hati. Orang Jawa jarang senyum yang dalam budaya Jawa disebut ngembang kacang (besengut:mbesengut) atau ngembang jambu (karuk:mleruk), sering kurang berpikir positif sehingga pantas direvolusi mentalnya. Orang yang gemar berpikir positif mentalnya tentu sehat. Mental sehat akan melahirkan insan yang berkarakter.
C. Panca Grahita Berpikir Positif Jawa
Para hadirin yang budiman,
Yang dimaksud panca grahita adalah lima hal yang membuat orang Jawa sadar diri (nggrahita). Panca berarti lima dan grahita berarti bangkit (wungu). Orang yang sadar diri dalam budaya Jawa disebut lantip ing panggrahita. Ungkapan panca grahita terinspirasi ungkapan Jawa tentang Panca Baya, artinya lima hal yang bahaya bagi manusia, berasal dari lima indera yaitu (1) pemandangan porno (cabul), (2) suara merdu, rayuan, (3) bau harum, (3) rasa enak, dan (5) sentuhan halus merangsang. Selain itu, orang Jawa juga memiliki ungkapan Panca Wisaya, artinya lima hal yang membahayakan hati. Lima hal itu terdapat dalam Serat Wulang Putri pupuh Maskumambang sebagai berikut.
Dhuh putrengsun sarnya sumurupa nini
Tegese kang panca
Wisaya mengko winardi
Ingkang sepisan rogarda
Maksudira garaning badan sayekti
Kalih sangsararda
Yeku rekasaning diri
Katelu ingkang winarna
Wirangarda tegese laraning ati
Kaping pat cuwarda
Yeku rekasaning ati
Durgarda pringganing nala
Dari lima hal (panca) yang menyebabkan hati sakit, yaitu (1) rogarda (badan sakit), (2) sangsarda (hati sengsara), (3) wirangarda (mendapat malu), (4) cuwarda (hati kecewa), (5) durgarda (hati yang kotor), tersebut saya muncul ide Panca Grahita, yang dapat menjadi obat penawar hati dengan cara berpikir positif. Panca grahita, berarti lima hal tentang grahitaning dhiri. Dalam konteks ini Supadjar (2001:308) menyebut orang Jawa yang sadar kosmis biasanya paham jati diri. Orang Jawa merasa paham jati diri, hatinya tergugah (nglilir), bagaikan gatra lelagon Ilir-ilir berbunyi “tandure wis sumilir”. Kondisi semacam ini, sudah dilukiskan dalam sebuah antologi geguritan karya Suripan Sadi Hutomo (1988) berjudul Angin Sumilir, yaitu keadaan manusia yang sadar kosmis, seperti sedang bangun dari tidur.
Keadaan mental semacam itu juga dilukiskan penggurit Aming Aminudin lewat karyanya berjudul Angin Sumilir, yang mengingatkan keadaan angin di sebuah desa, misalkan ada larik berbunyi: angin sumilir ing kampungku, ana antarane godhong-godhong tebu, gemrisik adhuh isise, adhuh segere, dene srengenge abang mbranang, saka kulon katon nyenengake. Geguritan ini menandai kesadaran diri penyair pada suasana alam pedesaan. Hal yang senada juga terjadi pada tokoh ki dalang Ki Darman Gunacarita dalam cerpen berjudul Petruk karya Jayus Pete (2001), ketika memandang tatahan wayang Petruk rusak dimakan anjing. Dia sadar diri ketika melihat suasana pohon kering, lalu mencipta Petruk versi bungkuk. Geguritan dan cerpen tersebut tergolong sastra antropologis. Maka dalam wawasan antropologi sastra suasana pikiran yang bangkit disebut osik ginugah, sebuah kondisi awas eling yang dalam lelagon Jawa Gandung Gandariya terpantul melalui ungkapan: E e e cao glethak, anjenggelek bali maneh atau maning, sebuah keadaan yang terjaga.
Menurut hemat saya, orang Jawa yang sudah mampu nglilir dan njenggelek, biasanya pikiranya lebih jernih sehingga suka berpikir positif. Njenggelek bali maneh, juga terkait dengan dorongan seksual, yang dalam budaya Jawa akibat adanya tirta kamandhanu, menjadi dorongan terbesar dalam hidup. Manakala tirta kamandhanu ini dikelola dengan berpikir positif, tentu akan tercipta kamalaras, bukan kamasalah. Berpikir positif adalah motor penggerak hidup yang menuju memayu hayuning bawana. Maka perkenankan saya menyebut bahwa berpikir positif ternyata sebuah pusaka sakti. Orang Jawa yang sakti, menandai digdaya tanpa aji, nglurug tanpa bala, dan menang tanpa ngasorake. Orang demikian kelak tergolong sekti mandraguna, artinya tidak terkalahkan karena memiliki ilmu (ngelmu). Ilmu berpikir positif Jawa menjadi filter kejiwaan, yang menciptakan suasana sekti mahambara. Untuk itu, orang Jawa sudah memiliki modal berpikir positif lima hal yang disebut Panca Grahita sebagai berikut.
Pertama, Teken tekun tekan (http://iwanmuljono.blogspot.com/2012, diakses 19 Nopember 2014). yang sering disingkat menjadi konsep 3-T. Teken berarti asalkan kita bertindak berlandaskan ilmu dan aturan, biarpun orang lain menganggap negatif, tentu akan tercapai. Tekun, artinya hati-hati dan rajin dalam menjalankan sesuatu. Tekan adalah ketercapaian. Dari konteks ini, orang Jawa yang berpikir positif akan selalu berusaha, biarpun banyak rintangan, tentu akan sukses.
Berpikir positif orang Jawa, sering saya dengar dari simbok saya menjelang tidur dengan lampu senthir. Masih terngiang sebuah lagu E Dhayohe Teka, Kidang Talun, Tikus Pithi, Cublak-Cublak Suweng, dan entah apalagi waktu itu sering dinyanyikan agak fals di depan tungku (luweng), sebagai sebuah restoran tradisional, sambil memegang cowek untuk makan sore. Ternyata, lewat restoran ngarep luweng itu, justru menggugah restorasi pemikiran saya, untuk menghayati cara berpikir positif simbok.
Kata beliau, E Dhayohe Teka yang memuat larik-larik berikut menjadi sumber pemikiran positif.
E dhayohe Teka
E gelarna klasa
E klasane bedhah
E tambalen jadah
E jadahe mambu
E pakakna asu
E asune mati
E guwangen kali
E kaline banjir
E guwangen pinggir
E pinggire jero
E tinggalen kono
(Tedjohadisoemarto, 1958:15)
Dhayoh dalam lagu tersebut multitafsir. Bertolak dari pemikiran tafsir Heidegger (Palmer,2005:46) lagu yang memuat dhayoh itu dapat dipahami atas dasar eksistensi manusia. Eksistensi manusia Jawa, sebaiknya berpikir positif terhadap dhayoh (tamu). Orang Jawa selalu berpinsip gupuh, lungguh, dan suguh ketika ada tamu, karenanya harus menyediakan tikar terbentang. Tamu tidak tentu berujud fisik manusia. Manusia menggali ilmu, hakikatnya juga menerima tamu. Tamu yang hadir prinsipnya harus sinuba siukarta, artinya disambut baik, tidak perlu berpikir negatif. Biarpun tamu itu kadang-kadang membawa cobaan, mengancam nasib, menusuk dari belakang, kita masih dianjurkan berpikir positif dengan konteks “guwangen kono” dan “tinggalen kono”.
Waktu itu simbok saya hanya hafalan belaka. Beliau telah mendorong saya berpikir positif lewat lagu itu, terutama ketika menghadapi dhayoh. Setiap saat kita akan menerima “dhayoh”. Cita-cita hidup itu dhayoh. Iman itu juga dhayoh. Bahkan setan pun dhayoh juga. Harapan beliau antara lain: (1) harus menyambut dhayoh dengan berpikir positif, yaitu menegakkan gupuh, lungguh, dan suguh dengan menyediakan tikar terbentang, (2) untuk menyambut dhayoh diri kita harus bersih, berpikir positif, seperti bentangan tikar, (3) manakala diri kita belum bersih, tikar itu ibaratnya tambalen jadah yang dalam bahasa Arab sering terdengar ungkapan dari Bapak Rektor dalam beberapa sambutan acara penting di UNY: Man jadda wajada bermakna "siapa saja yang berusaha (Insya Allah) akan mendapat apa yang diusahakannya. Begitu pula Man zara'a hasada, artinya siapa yang menanam (Insya Allah) akan menuai hasilnya. Ungkapan itu, dalam konteks budaya Jawa, berbunyi sapa gawe nganggo dan sapa nandur ngundhuh.
Jadah berasal dari ketan (raketan), artinya sambutlah tamu dengan semangat persaudaraan, merapatkan hubungan silahturahmi satu sama lain, yang bukan sekedar lamis (di luar mengaku saudara, ternyata hatinya busuk). Maka lantunan lelagon Jawa berjudul Aja Lamis, layak dicamkan bahwa: Aja sok gampang dadi wong manis, yen ta amung lamis, becik aluwung prasaja Nimas ora agawe gela….mbok aja amung lamis kang uwis dadine banjur dhidhis…(Saprodjo, 2002:1). Dari sepenggal lagu ini, dapat dihayati bahwa orang suka lamis (semu), biasanya enggan berpikir positif. Ternyata, setelah saya dalami dengan perangkat permainan tafsir di program studi Antropologi UGM, secara antropologi sastra lagu itu menandai bahwa lamis adalah hidup yang serba lipstick.
Dengan gigih saya ngangsu kawruh pada para Begawan budaya, bapak Prof. Dr. Syafri Sairin, MA, yang kuliah hanya berdua di ruang kerjanya, saya semakin terbuka. Waktu itu, dia membebaskan tafsir sebuah telur lewat baca buku mini berjudul The Silent Language. Pijaran buku kecil itu, membuka cakrawala tafsir saya ketika memahami lelagon Jawa yang banyak mengajak berpikir positif. Lebih mantap lagi ketika saya belajar tafsir postmodernisme dari Bapak Prof.Dr. PM. Laksono, MA, katanya makna itu boleh dikreasi, dengan membangun konteks. Gempuran akademik beliau berdua, rasanya telah menjebol sekat-sekat tafsir saya yang seringkali masih berada di bawah tempurung hitam. Dengan sentuhan perkasa di ruang Pusat Studi Asia Pasifik UGM, beliau selalu mengatakan: “Tafsir kamu harus kempel, jangan kempyah (seperti bakpia), jangan sekedar binder, comot sana sini.” Untaian resep semacam ini selalu saya pegang, karena dalam ilmu Barat jarang saya temukan. Di beberapa ilmuwan budaya Barat, seperti Geertz, Turner, dan Siegel, tafsir budaya selalu dianggap bermutu (ora baen-baen).
Apalagi ketika saya masuk gedung Antropologi FIB UGM, ke ruang kecil Bapak Prof. Dr. Suhardi, MA. yang benar-benar ahli kejawen, terbuka lebar pemaknaan saya terhadap sejumlah fenomena budaya Jawa. Kata beliau yang masih selalu saya ingat: “Boleh saja memaknai budaya Jawa dengan membuat carangan-carangan, asal jangan ngawur, tulislah jangan seperti menulis di koran.” Resep keilmuan beliau itu menurut hemat saya sebuah revolusi mental akademik. Maksudnya, menengok ilmu Barat tidak salah untuk memaknai Jawa, tetapi di Jawa sesungguhnya kaya, seperti sebuah sumur, semakin digali semakin jernih. Saya jadi sering ingat dengan diskusi kritis dengan Kang Minto, senior saya, di parkiran, teras, dan lab karawitan, sambil menyedot rokok. Beliau selalu memanggil akrab saya “Dek”, disertai pemanis akademik: Jawa ki jero Dek, kudu ngerti mangasah mingising budi, ngerti konthol Adam, lan Jajak Wreka, Resi Maenaka, ora kabeh kok tulis.”
Dari percikan para pepundhen tadi, saya merasa digembleng. Biarpun kadang-kadang panas telinga saya, tetapi saya justru tergugah harus membuktikan semua itu. Saya merasa sedang belajar berpikir positif, maksudnya biarpun beliau-beliau tadi meluncurkan pil-pil pahit, saya yakin bermasud baik. Hidup itu sering berbeda dengan angan-angan kita.
Kedua, Sing uwis ya uwis, adalah teks budaya berpikir positif ala Jawa. Konteks ini tidak mudah implementasinya dalam kehidupan nyata. Terlebih lagi ketika kita menghadapi “Wong Jawa jawal, jawane kadhal”. Dari sisi antropologi sastra Jawa, ada geguritan berjudul Wong Jawa karya Suripan Sadi Hutomo yang memuat nuansa berpikir positif dan negatif.
Wong Jawa: Suripan Sadi Hutomo
wong Jawa aja jawal
Jawa jawal jawane kadhal
apa sliramu Jawa, mitraku
geneya kok ngiris atiku
(Antologi Puisi Jawa Modern 1940-1980, 1984:100, bait satu)
Berhadapan dengan karakter wong Jawa jawal, sungguh tidak mudah. Orang yang jawal, biasanya berperilaku bengis (tegelan). Ciri orang kejam, jika kentut bunyi dan dikibaskan pada orang lain. Jika bicara gemar bisik-bisik. Jawal, adalah perilaku yang menyimpang dari aturan Jawi (kejawaan). Sebenarnya dia itu sudah tidak njawani perilakunya, meskipun mengaku orang Jawa. Perilakunya sering kelihatan halus, tertawa terbahak-bahak, namun hatinya berduri (jawal). Jawal berarti suka menjegal sesama. Mereka biasanya merasa susah jika ada pihak lain mendapatkan kesenangan. Mereka bersifat dengki, srei, jail, methakil, seperti kadhal. Kadhal, adalah hewan melata yang suka mencari orang lain terlena (nglimpe). Terlebih lagi kalau sudah kategori “kadhal buntung”, amat berbahaya jika kita tidak berpikir positif. Orang Jawa demikian, layak direvolusi mentalnya. Mental orang Jawa jawal dan kadhal, biasanya berbudaya SMS, kependekan dari senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang.
Hadirin yang terhormat,
Sungguh sangat memalukan dan memilukan orang-orang yang sedang terkena penyakit “jawa jawal”. Virus yang mereka idap, melebihi virus ebola dan flu burung. Maksudnya, virus itu sering menular dengan konsep Jawa mencari teman (golek bala). Teman yang senasib, sering menggunjing dan mencari-cari kesalahan pihak lain yang dianggap musuh (satru).
Gaya hidup orang itu, jika belum meninggal (dikucir), masih mengalir kotor di tengah-tengah kehidupan. Pikiran positif dan negatif memang menular. Setiap dari kita mempengaruhi orang-orang yang kita temui, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terjadi secara naluriah, dalam pikiran bawah sadar manusia, yang terpancar melalui pikiran dan perasaan, serta bahasa tubuh kita. Orang di sekeliling kita dapat merasakan aura kita dan dipengaruhi oleh pikiran kita, juga sebaliknya. Wajarkah jika kita ingin berada di sekitar orang-orang yang positif dan menghindari orang-orang yang negatif? Orang lebih tergerak untuk membantu kita jika kita bersikap positif, dan mereka tidak menyukai dan menghindari siapapun yang bersikap negatif.
Berpikir positif adalah ruh yang membimbing manusia memiliki budi luhur. Setelah saya dalami bertahun-tahun jagad sastra Jawa, tidak sedikit yang memiliki katarsis berpikir positif. Maksudnya, yang telah terjadi ya sudah tidak perlu diungkit-ungkit, melainkan dijadikan bahan: (a) SD, kependekan dari sadar diri. Sadar diri adalah kemampuan mawas diri, agar ke depan tidak terulangi hal-hal yang pahit, sebab ada adagium kuda saja tidak mau terantuk batu dua kali, (b) SMP, kependekan dari sistem manajemen pribadi, yang mengarahkan diri pribadi yang dapat menjadi pengelola hidup sesungguhnya, orang lain hanya sebagai tambahan saja, (c) SMA, kependekan dari sistem manajemen ati, artinya upaya untuk menata hati sanubari, agar selalu menep (tenang) menghadapi segala cobaan. Hal semacam ini terungkap melalui geguritan berjudul Wengi Ing Pinggir Bengawan, yang melukiskan Adipati Karno berhadapan dengan Dewi Kunti, ketika akan melawan Arjuna pada Perang Baratayuda.
Wengi ing Pinggir Bengawan: Moch Nursyahid P
-Oh, ora bisa, dhuh Kunthi ibuku
kasunyatan aku mung anak kusir Adirata sing sudra papa
kang ora kepengin ngranggeh kaluhuran sing ngliwati ukuran
taline katresnan kang wis dipunthes kanthi peksan
langka bisa bali pulih karana manising janji lan pangiming-iming
apamaneh mung dipameri runtuhing eluh kang wis kadaluwarsa
asor banget budiku ngaku-aku anake raja-raja sinatriya kang ambeg
utama
mula rilakna aku bakal ayun-ayunan ing alaga karo Arjuna
+dhuh anakku kang tuhu berbudi
geneya kowe nduwa panjaluke ibu
kaya wis dadi pesthine dewa, aku bakal nyangga dosa tumekeng pati
bibit kaluputan mung sawiji sawi
jebul ngrembaka dadi gedhe sundhul wiyati…..
(Antologi Puisi Jawa Modern 1940-1980, 1984:113, bait 11-12)
Dari geguritan tentang wayang tersebut, dapat diketahui cara berpikir positif orang Jawa. Cara berpikir Karna, yang menolak ajakan ibunya, dilandasi pula sebuah alasan bahwa di mata Karna, seorang ibu tentu tidak mungkin tega terhadap anak sendiri yang dalam budaya Jawa disebut kulit daginge dhewe. Mental Karna menolak ajakan Dewi Kunti jelas berdasarkan nalar jiwa pahlawan (altruistik). Kepahlawanan Karna, termuat dalam Serat Tripama bait 6 karya KGPAA Mangkunagara IV, berbunyi: Minungsuhken kadange pribadi, aprang tandhing lan sang Dananjaya, Sri Karna suka manahe, dene sira pikantuk, marga dennya arsa males-sih,ira sang Duryudana. Tembang ini menunjukkan bahwa Karna lebih mandahulukan kepentingan negara di atas kepentingan diri, terutama dalam konteks balas jasa. Mental Karna demikian juga sejalan dengan lagu (gerongan) “Brambang sak sen lima, berjuwang labuh negara.” Perilaku Karna tadi disebut laku utama oleh orang Jawa. Lebih hebat lagi bila “Brambang sak sen papat, berjuwang kudu makrifat”, maksudnya berjuang tanpa pamrih.
Orang Jawa memiliki paradigma berpikir positif isih untung (begja), yang dalam wejangan Ki Ageng Suryamentaram disebut kawruh begja. Begja, juga dialami seorang Karna dan Dewi Kunti. Bagi Kunti, masih untung bisa bertemu ibunya biarpun awalnya merasa terbuang. Bagi Dewi Kunti, juga berpikir positif, biarpun anaknya menolak bersatu dengan Pandawa, mungkin itu sebuah pilihan hidup. Konsep begja itu memberikan spirit mental agar orang Jawa tidak senantiasa nutuh, artinya menyalahkan orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Seringkali kalau kita sedang mendapatkan musibah, misalkan diserempet, ditabrak, dan tabrakan banyak yang selalu berujung ke polisi. Banyak pula yang berujung sampai pengadilan. Begitu juga kalau kita dikhianati orang-orang dekat, sungguh sakit dan pedih.Namun, apabila kita sikapi dengan berpikir positif, tentu tidak akan berlanjut sampai kebencian yang berbahaya. Jika kita berpikir negatif, hanya akan melahirkan (a) kedengkian, (b) kejengkelan, dan (c) ketegaan, dan ada kalanya berujung sampai pembunuhan. Konteks isih begja, akan menenangkan hati, sebagai revolusi mental amarah menuju mutmainah.
Mental amarah, sama halnya dengan mental harimau. Yakni mental kotor yang ingin menang sendiri, ingin menguasai orang lain. Mental ini sering dimaknai dengan perilaku drengki, srei, jail, methakil, dan mbedhidhil. Orang demikian, biasanya berkarakter: (1) selalu menganggap kecil orang lain. Orang lain dianggap lemah, ingin disantap (dimangsa), (2) selalu ingin menguasai orang lain dengan berbagai dalih, (3) menyalahkan (metani liyan) terus pihak lain dan menganggap dirinya yang paling benar, paling hebat, paling top, dan tiada tanding.
Hadirin yang budiman,
Ketiga, Ana dina ana upa, yen obah mamah adalah ungkapan berpikir positif orang Jawa. Ungkapan demikian boleh dikatakan sebagai refleksi berpikir positif tentang optimisme Jawa. Pikiran-pikiran yang positif akan membuat hidup manusia semakin mudah mengarungi jalan hidup. Jika Manusia selalu diselimuti pikiran-pikiran yang positif, maka jiwa manusia semakin tenang. Selain itu, kita tidak lagi dikejar-kejar oleh apa yang tidak manusia suka dalam hidup. Oleh karena apa yang belum dicapai dan berbagai pikiran negatif yang pada akhirnya membuyarkan fokus dan mimpi yang ingin dicapai. Pikiran negatif akan menjadi hantu pikiran. Dalam lelagon rakyat jaman dahulu, sering kita dengar berjudul Sepur Truthuk.
Numpak sepur truthuk wiwit wayah esuk
Nganti wayah sore durung tekan nggone
Adhuh lae adhuh lae
Le bola-bali mandheg, ugreg-ugreg ugreg-ugreg
Saben bakul diendhegi
Neng edhung eneng telep neng dhung neng crut
Suwe-suwe suwe-suwe mudhun sepur
boyok pegel dhuwit entong, tut tut greg tut-tut pipis
(Gending Dolanan, Arintaka, 1984:10)
Lagu tersebut merupakan cara berpikir positif yang selalu optimistis terhadap sebuah usaha. Sepur truthuk, secara historis jelas pernah ada. Perjalanan hidup manusia, tidak jauh berbeda dengan orang yang sedang naik kereta. Dalam proses kehidupan, manusia sering berhenti, tergoda penjual di kereta, dan akhirnya akan sampai tujuan. Ketika orang naik kereta, sebaiknya tidak mengenal lelah. Ketika kereta itu berkali-kali berhenti, sering membuah keluh kesah diri. Menyikapi keadaan demikian yang penting ada upaya, bahwa pada saatnya akan sampai. Daripada menyesali dan mengiba pada kemalangan nasib, sebaiknya manusia harus mulai membiasakan diri untuk selalu berpikir positif dan memotivasi diri bahwa di balik resiko, ada hikmahnya. Setiap kali kita mengawali aktivitas, berdiri di depan cermin lalu mengucapkan sugesti positif untuk diri sendiri. Manusia bisa membuat sugesti yang diinginkan. Dengan memberi sugesti positif pada diri sendiri, maka suatu saat akan terheran-heran dengan hasilnya. Dalam lagu (sastra karawitan) berjudul Plek-Emplek Ketepu, sebagai berikut tampak sebuah sugesti orang berpikir positif.
Buka Celuk: Plek emplek ketepu wong lanang goleka kayu.
Allah wayah golek pisan allah wayah golek pisan
O e o golek pisan o e o
Lamun golek wong lanang mbok ajalah menek
Allah menek menek pisan allah menek menek pisan
O e o menek pisan o e o
Lamun menek wong lanang mbok aja dhuwur
Allah dhuwur dhuwur pisan allah dhuwur dhuwur pisan
O e o dhuwur pisan o e o
Lamun dhuwur wong lanang ajalah mencit
Allah mencit mencit pisan allah mencit mencit pisan
O e o mencit pisan o e o
Lamun mencit wong lanang ajalah tiba
Allah tiba tiba pisan allah tiba tiba pisan
O e o tiba pisan o e o
Lamun tiba wong lanang ajalah lara
Allah lara lara pisan allah lara lara pisan
O e o lara pisan o e o
Lamun lara wong lanang ajalah mati
(Widodo dan Sutarno, 1995:97)
Lagu tersebut, mengarahkan manusia berpikir positif dan hati-hati. Pikiran positif tampak pada sebuah imajinasi seseorang yang sedang berusaha mencari kayu. Kayu, dalam konteks wayang kulit disebut kayon, seperti dalam kisah Dewa Ruci tentang ungkapan golek kayu gung susuhing angin. Kayu (kayun) berarti hasrat hidup.Ada juga istilah kayu purwa sejati, yang menyimbolkan eksistensi dunia mistik kejawen. Pada tataran itu, bila manusia mencari kayu (hayun), artinya hidup, tidak harus menek (memanjat), bila memanjat jangan sampai pucuk, jika ke pucuk jangan sampai jatuh, jika jatuh jangan sampai sakit, dan apabila sakit jangan sampai mati. Hal ini menandai bahwa hidup itu penting dan perlu dikelola dengan hati-hati. Yang penting dalam hidup harus bergerak (obah) dan berupaya keras (mosik) mencapai ketenteraman.
Tanda jika orang itu hidup, dalam budaya Jawa seperti dalam lelagon Sluku-sluku Bathok berbunyi: Nek obah medeni bocah, nek urip goleka dhuwit, yang konon berasal dari silap dengar (Endraswara, 2010:56) mahabatan mahrojuhu taubatan. Mahabatan artinya senang kepada Tuhan agar selalu dikasihi. Agar selalu dicintai Allah, harus mahrojuhu yaitu mencari dalan padhang (berbuat baik) dengan jalan tobat (taubatan). Dengan tobat, manusia akan mengetahui sangkan paraning dumadi, yakni seperti dalam gatra lagu nek urip goleka dhuwit (yasrifu inna khalaqnal insana min maain dhofiq). Kata yasrifu berarti bahwa manusia harus ingat terhadap kemuliaan, manusia dapat hidup mulia karena mengetahui asal-usul hidupnya. Manusia yang dikaruniai derajat mulia itu, sebenarnya awal kejadian manusia hanyalah dari dhofiq (air mani). Maksudnya, dari cairan yang demikian, ternyata manusia justru menjadi lebih tinggi derajatnya. Karena itu harus disadari.
Ada lagi yang berpendapat bahwa larik mak jenthit loloba berasal dari ittaqillaha robbah, artinya dadekna Pangeran Allah, aja nyembah sakliyane. Wong mati ora obah, dari ungkapan man maata roaa dzunubahu, artinya wong mati weruh dosanira dhewe. Berkaitan dengan hal ini, sejak manusia masih obah (hidup) harus bergerak, untuk menemukan keselamatan. Obah, artinya bergerak sebagai tanda hidup. Orang yang bergerak biasanya menggambarkan orang mau berpikir. Pada situasi tertentu manusia yang berusaha sesuatu bisa mengeluh, maka buatlah kondisi tersebut sebagai sesuatu yang patut disyukuri. Jika ada rintangan, anggap saja sebagai cambuk, bukan sebaliknya mudah putus asa. Membayangkan apa yang diinginkan seperti memanjat pohon, asalkan hati-hati, akan selamat.
Berpikir positif semacam ini merupakan sikap mental yang melibatkan proses memasukan pikiran-pikiran, kata-kata, dan gambaran-gambaran yang konstruktif (membangun) bagi perkembangan pikiran manusia. Itulah sebabnya dalam laku Cublak-cublak Suweng terdapat larik berbunyi sir-sirpong dhele gosong, berasal dari sirion dalan sowaban. Maksudnya menempuhlah jalan yang benar. Pikiran positif menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, serta kesuksesan dalam setiap situasi dan tindakan manusia. Apapun yang manusia harapkan, pikiran positif akan mewujudkannya. Jadi berpikir positif juga merupakan sikap mental yang mengharapkan hasil yang baik serta menguntungkan.
Hadirin yang berbahagia dan sabar
Keempat, Wis ana sing ngatur, adalah ungkapan berpikir positif Jawa ketika menghadapi suasana dunia yang serba berebut. Banyak perebutan kursi, dari tingkat pemerintahan yang paling rendah sampai ke pejabat tinggi, sering memunculkan friksi di sana sini. Bahkan pasca perebutan pun sering masih terasa getahnya. Ada di antara mereka yang sampai tidak mau bertemu (papasan), tidak mau berbicara (neng-nengan), dan akhirnya tidak mau bertegur sapa (njothak).
Itulah hati Jawa, yang belum paham berpikir positif, padahal semua hal itu sesungguhnya wis ana sing ngatur. Artinya, bahwa segala sesuatu yang terkait dengan nasib itu ada yang mengatur, yaitu Kang Gawe Urip. Namun kita sering lupa pada ajaran leluhur Jawa itu. Orang Jawa senantiasa memiliki falsafah bahwa (1) siji pati, (2) loro jodho, dan (3) telu tibaning wahyu, wus ginaris. Garis itu memberikan penegasan bahwa manusia Jawa sesungguhnya tidak perlu harus berpikir negatif pada orang lain. Konsep filosofi Jawa bahwa manusia mung saderma. Perebutan jabatan adalah bagian dari tibaning wahyu, sehingga tidak harus berlarut-larut sampai berpikir negatif pada lawannya. Oleh sebab itu, dalam lelagon di bawah ini pantas dijadikan pegangan orang yang senantiasa berpikir positif.
Te Kate Dipanah
Te kate dipanah
Dipanah ngisor gelagah
Ana manuk ondhe-ondhe
Mbok sir bombok mbok sir kate
(Widodo dan Sutarno, 1995:69-70)
Segala tindakan perlu dipikirkan secara positif dengan penghayatan batin mendalam (dimanah). Jika tanpa dimanah manuk ondhe-ondhe akan semakin sulit menemukan kayu gung susuhing angin. Maksudnya, percikan air kendhi yang benar-benar suci (mulia) sulit menuntun tercapainya sir (sri) dan kate (tekat). Sir berarti jalan dan tekat artinya keinginan. Jalan dan keinginan, selalu bersimpangan banyak, penuh pilihan. Hidup ini selalu harus menjatuhkan pilihan. Pilihan itu tidak boleh meleset dari kayu (hayu), artinya hidup sejati ketika menemukan susuhing angin. Banyak alternatif yang dapat mengantarkan manusia mencapai keselamatan. Jika jalan dan keinginan itu dilandasi berpikir positif, orang Jawa akan semakin mudah jalan hidupnya.
Kita sering mendengar orang berkata: “Berpikirlah positif!”, yang ditujukan bagi orang-orang yang merasa kecewa dan khawatir. Banyak orang tidak menganggap serius kata-kata tersebut, karena mereka tidak mengetahui arti sebenarnya dari kata-kata tersebut, atau menganggapnya tidak berguna dan efektif. Dalam sebuah dongeng Jawa berjudul Kancil Kepengin Mabur Akibatnya dia menemui kecelakaan atas ulah seekor monyet yang balas dendam, karena pernah diperdaya kancil. Memang ada baiknya, kancil lebih berpikir positif pada perilaku monyet. Namun berpikir positif demikian tidak diimbangi oleh kehati-hatian (dimanah), agar selamat. Kancil pun tanpa dihantui oleh pikiran-pikiran negatif dan rasa takut mengikuti perintah monyet. Kancil waktu itu diikat tali, dipasangi sayap seakan-akan bisa terbang, lalu tali dilepaskan, jatuhlah dia ke kolam yang dalam.
Jika kita memiliki sikap yang positif, sikap-sikap tersebut akan menghasilkan perasaan-perasaan yang positif, gambaran-gambaran yang konstruktif, dan kita akan melihat dalam mata pikiran kita apa yang kita inginkan. Hal ini akan memberikan pencerahan, lebih banyak kekuatan, dan kebahagiaan. Diri manusia juga akan memancarkan kebaikan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Bahkan pikiran positif juga akan memberikan beragam manfaat bagi kesehatan manusia. Kita berjalan tegak dan suara kita lebih berwibawa. Bahasa tubuh kita menunjukkan perasaan kita.
Hadirin yang budiman,
Kelima, Gusti ora sare. Perkenankan saya berdiri di mimbar emas ini, untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Allah SWT, yang benar-benar bahwa “Gusti ora sare”, karena usulan Guru Besar ini telah melalui perjalanan panjang, melelahkan, ada lilitan tali-temali yang siap menjerat, penuh kerikil tajam di kanan kiri kaki, bahkan banyak duri mengancam, namun akhirnya terasa “plong”, setelah lewat bimbingan guru sejati yang bersinar, menuntun pepadhang sak sada lanang, sehingga turun wahyu dyatmika.
Wahyu dyatmika yang muncul, yaitu adanya keinginan merevolusi mental dari pikiran negative menjadi berpikir positif. Berpikir positif adalah mencoba mengambil hikmah dari kejadian yang pahit, penuh kepasrahan. Hal itu penting, sebab dalam parikan Jawa sudah cukup jelas terungkap bahwa “kecipir mrambat ing wit kara, yen dipikir marahi lara.” (Soebagyo, 1992:15). Artinya, jika dalam perebutan apa pun atau cobaan hidup, selalu dipikir secara negatif, dapat menyebabkan penyakit. Berpikir positif bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur, artinya selalu memperhatikan upaya seseorang yang jernih, perlu di kedepankan. Maka upaya memfokuskan diri pada pikiran-pikiran yang positif dan menyenangkan sangat penting. Kendala dalam setiap langkah, seringkali tidak terduga, yang penting kita berpikiran positif pada pihak lain yang sering mengganggu langkah kita. Pikirkan hasil serta situasi yang menguntungkan manusia, dan keadaan akan berubah sesuai dengan pikiran manusia. Perubahan ini tentunya membutuhkan waktu, namun pada akhirnya perubahan akan terjadi.
Perlu diketahui bahwa pikiran-pikiran, kata-kata, dan sikap negatif akan menghasilkan mood serta tindakan yang negatif dan tidak menyenangkan. Semua hal ini akan berujung pada kegagalan, frustrasi, dan kekecewaan. Untuk merubah pikiran manusia menjadi positif, diperlukan latihan dan kemauan untuk merubah diri manusia karena sikap dan pola pikir tidak dapat berubah dalam sekejap. Kekuatan pikiran merupakan kekuatan dahsyat yang selalu membentuk kehidupan kita. Proses pembentukkan biasanya dilakukan di dalam pikiran bawah sadar kita, namun sangatlah mungkin untuk melakukan proses tersebut secara sadar. Meskipun usulan tersebut terdengar cukup aneh; cobalah untuk melakukannya, karena manusia tidak akan merasa rugi; sebaliknya manusia akan memperoleh banyak hal. Acuhkan apapun pendapat orang lain tentang diri manusia ketika manusia mengubah pola pikir manusia.
Gunakan kata-kata positif dalam suara hati manusia atau ketika manusia berbicara dengan orang lain. Tersenyumlah sedikit lebih banyak, karena senyuman akan membantu manusia untuk berpikir lebih positif. Abaikan perasaan malas atau keinginan untuk berhenti. Jika manusia bertahan, manusia akan berubah pola pikir manusia. Saat pikiran negatif memasuki pikiran manusia, manusia harus mewaspadainya dan menggantikan pikiran tersebut dengan pikiran yang lebih konstruktif. Pikiran negatif akan mencoba memasuki pikiran manusia lagi, dan sekali lagi manusia harus menggantikannya dengan pikiran positif.
Mengubah energi berpikir negatif ke berpikir positif, tidak seperti orang membalik telapak tangan. Energi positif merupakan mesin pemikiran orang Jawa yang apabila dikelola, akan mengantarkan sampai tingkat keselamatan (Endraswara, 2011;10). Berpikir positif sebenarnya ada dalam diri setiap orang Jawa. Berpikir positif memang belum banyak dibiacarakan orang dalam berbagai forum. Padahal, berpikir positif itu sesungguhnya menyehatkan badan. Tanggal 22 Juni 2009, saya diundang Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di hotel Purosani Yogyakarta, yang terkenang saya diberi sebuah buku oleh menteri Jero Wacik, berjudul Berpikir Positif. Waktu itu, spontan langsung saya mintakan tanda tangan beliau. Ternyata, pikiran dia dalam buku itu, mengilhami angan-angan saya untuk membuka tabir berpikir positif orang Jawa. Biarpun cara berpikir beliau jelas ala Bali, ternyata ada kemiripan dengan orang Jawa.
Yang menarik, Wacik (2010:11-195) menulis cara berpikir positif dalam hidupnya yang kompleks, mulai persoalan keluarga, sekolah, bergorganisasi, asmara, politik, hingga dia mampu menjadi menteri berkali-kali. Inti berpikir positif dia adalah sebuah cara pandang dengan selalu melihat dan menekankan sisi positif dari apa pun yang terjadi di sekitarnya. The power of positive thinking menjadi landasan konseptual. Kalau begitu berpikir positif tidak jauh berbeda dengan pandangan hidup seseorang. Pandangan hidup itu akan menjadi motor dalam perjalanan hidup seseorang.
D. Catur Gatra Menuju Revolusi Mental Bangsa
Hadirin yang terhormat,
Catur gatra berasal dari inspirasi ungkapan catur purusa dan catur dhendha. Catur berarti empat, catur purusa ada empat ajaran kepemimpinan, yaitu (1) sama, (2) beda, (3) dana, dan (4) dhendha. Catur dhendha berarti perempatan jalan. Pada waktu orang Jawa mempunyai hajat wiwahan manten, jika sudah selesai biasanya membuang sekar manca warna. Ungkapan yang sering terdengar yaitu “Yen wus paripurna wohing gati, Sekar Mancawarna, kedah winangsulaken ing pagan kang maligi ya ing catur dhendha/marga catur ya kang sinebut prapatan nering pangesthi: Mbuwang sukertaning Sri Panganten sarimbit.
Dari konsep catur dhendha tersebut saya muncul ungkapan catur gatra. Gatra berarti hal, buah, baris, dan sejenisnya. Dalam kehidupan orang Jawa ada empat hal yang dapat dijadikan wahana revolusi mental yang disebut catur gatra. Revolusi mental (maaf, meminjam istilah Widodo, Kompas (Hal. 6), Sabtu (10/5/2014) memang sudah saatnya diwujudkan. Maksudnya, sebuah dunia masa depan yang bebas dari asap pesimistis. Masa depan bangsa yang tidak terkotori oleh mental keruh yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan lokal. Terminologi "revolusi", kata Widodo, tidak selalu berarti perang melawan penjajah. Menurut dia, kata revolusi mental merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya. Kalau ada kerusakan tentang nilai kedisiplinan, ya mesti ada serangan nilai-nilai ke arah itu.
Menurut hemat saya, cara berpikir positif merupakan pangkal tolak revolusi mental. Revolusi mental juga berarti refleksi mental dan sekaligus restorasi mental. Dalam mengisi pembangunan bangsa, sudah saatnya melakukan tindakan korektif, yang dalam budaya Jawa disebut mawas diri. Berkaitan dengan hal ini ada empat hal yang saya sebut catur gatra, yang perlu dilakukan revolusi mental Jawa.
Pertama, mental konsumeristik Jawa. Konsumerisme sebagai gejala budaya lahir dari perubahan struktur lingkungan yang memaksakan hasrat tertentu agar menjadi kebiasaan sosial. Misalnya, kebiasaan berbelanja sebagai gaya hidup dan bukan karena perlu, atau menilai prestise melalui kepemilikan benda bermerek luar negeri. Hal semacam ini jelas sebuah mentalitas bangsa, yang kadang-kadang perlu diubah.
Ayam paling ingin disanjung
Mental konsumeristik Jawa menandai hadirnya gaya hidup yang serba glamour. Jika mental konsumeristik itu semakin menjadi-hadi, akan menjadi orang yang mendem pengalem, artinya gila pujian. Sanjungan yang terkait dengan harta kekayaan atau kepemilikan selalu menjadi idola hidupnya. Dalam crita cekak berjudul Semilyar karya Senggono (Jaya Baya, 7 April 1991), memberikan lukisan hidup konsumeristik yang ingin diwah. Seorang tokoh cerita cekak bernama Glompong dianggap gila, lalu berjalan kemana-mana. Dia ingin diwah, lalu berhutang uang sampai semilyar, untuk membeli berbagai perabot dan kendaraan. Dia sambil melagukan zaman edan versi R Ng. Ranggawarsita berjalan terus menyusuri toko: amenangi zaman edan, nlangsa temen awak iki, dhit semilyar sida amblas, bojo siji anginggati, edan edan lan sinthing, edan gemblung edan gemblung, lha sapa sing edan, ora edan ora sinthing, mung semilyar sida gemblung sida edan. Maksud dari tembang ini menjadi saksi zaman konsumeristik, semua hal serba ingin baru, ternyata uang hasil pinjaman itu remuk tercuci.
Crita cekak tersebut menggambarkan dan juga mengkritik “mentalitas zaman” yang serba ingin dipuji. Hal senada juga dapat terjajdi pada mentalitas pejabat, dosen, mahasiswa, petani, mentalitas industrial, mentalitas priyayi, dan sebagainya yang gemar belanja serba mewah. Bahkan seringkali terjadi orang belanja barang tetapi tidak terpakai. Pakaian berpuluh-puluh dibeli, tetapi tidak dipakai, hanya disimpan di almari. Dengan demikian mental Jawa yang serba ingin wah (mewah), tampak gemerlap itu pantas direvolusi. Revolusi mental konsumeristik menjadi mentalitas produktif dan kreatif memang membutuhkan waktu.
Mental konsumeristik kurang elegan dibanding mental tempe.Mental konsumen itu cenderung sebagai pengguna, bukan produktif. Mental tempe masih lebih bagus, karena berupaya memproduksi dan berkreasi. Mulai dari bungkus daun sampai bungkus plastik, dari mendoan, tempe bacem, tempe garet, sampai kripik tempe sudah merujuk pemberdayaan otak kanan. Namun demikian otak tempe itu, dianggap lembek, dan tidak tahan busuk. Itulah sebabnya, untuk merevolusi mental konsumeristik perlu melakukan dekonstruksi budaya tempe.
Kedua, mental materialistik Jawa. Orang Jawa selalu menggunakan pemikiran (mentalitas) ana rega ana rupa dan jer basuki mawa beya yang apabila salah tafsir sering mempengaruhi mentalitas materialistik. Hal ini dapat disaksikan dalam perhelatan manten sering kita mendengarkan seorang pemberi petuah (sabdatama) dengan tembang asmaradana: gegarane wong akrami, dudu bandha dudu rupa amung ati pawitane, ternyata sekarang sudah berbubah. Masyarakat Jawa sudah gegarane wong akrami, kudu bandha kudu rupa amung mobil sakuncine. Perubahan kata pada tembang yang dikutip dari Serat Menak Cina itu, menandai perlunya revolusi mental yang disebut back to basic. Mental orang Jawa yang mulia merambah mental material, selayaknya dikembalikan (direvolusi) ke mental spiritual.
Mentalitas Jawa yang materialistik adalah genangan segala sesuatu menyangkut cara hidup, yang kadang-kadang menjerumuskan kehidupan masyarakat. Di dalam cara hidup ada cara berpikir, cara memandang masalah, cara merasa, mempercayai/meyakini, cara berperilaku dan bertindak yang selalu diukur dengan materi, akan melenyapkan semangat spiritualistik. Fenomena gotong royong, sambatan, dan guyup rukun di wilayah Jawa, semakin merosot boleh jadi juga dipengaruhi oleh mental bendawi (material).
Daya-daya mental seperti bernalar, berpikir, membuat pertimbangan dan mengambil keputusan memang tidak ragawi (tidak kasat mata), tetapi dunia mental tidak mungkin terbangun tanpa pengalaman ragawi. Pada gilirannya, daya-daya mental pun dibentuk dan menghasilkan perilaku serta tindakan ragawi. Kelenturan mental, yaitu kemampuan untuk mengubah cara berpikir, cara memandang, cara berperilaku/bertindak juga dipengaruhi oleh hasrat (campuran antara emosi dan motivasi).
Ketiga, mental buta. Mental buta jelas berbahaya bagi kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kekeliruan memahami pengertian mental (dan bahkan ada yang menyempitkannya ke kesadaran moral) membuat seolah-olah perubahan mental hanyalah soal perubahan moral yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal ragawi. Mengubah mental buta menjadi mental satria, jelas butuh revolusi yang panjang. Mari kita renungkan watak jelek orang Jawa, yang tercitra lewat perang kembang. Hal ini pernah saya sampaikan ketika membahas Perang Kembang di Seminar Nasional FIB UGM, 11 Desember 2010 bahwa mental buta memang beroposisi biner dengan tokoh satria. Mental buta selalu berwatak tamak, ingin menang sendiri, dengan semangat nguntal malang dan prajaga belah jeg-jegan.
Kalau saya menonton perang kembang, langsung ada dua komentar yang muncul: (1) itu lukisan kegemaran mimpi buruk orang Jawa dan (2) ternyata orang Jawa itu pembohong, atau sebut saja munafik Jawa. Antara Jawa dan Islam senantiasa berjalan seiring. Mimpi buruk dan bohong saling melilit dunia orang Jawa, seperti adegan Bambangan-Cakil. Bayangkan, (1) ketika buta (Cakil) dinyatakan angkara, Bambangan (Arjuna, Irawan, Angkawijaya) dianggap santun, yang terjadi di Jawa justru sering paradok. Maksudnya, tak sedikit Bambang yang lebih Cakil dari Cakil. Bambangan yang di masyarakat berbaju, berdasi, tetapi justru lebih angkara murka; (2) belum lagi watak bohong dan pura-pura para satria, dalam bahasa Jawa “wis ora ketulungan”, inilah tragedi terberat orang Jawa. Bohong adalah dunia sandiwara, jagad teater dalam istilah Geertz (2000). Dalam perang kembang, selalu muncul gerak-gerak unik, misalkan seorang satria berkata: krasa tangan, kramasi epek-epek, dan lain-lain. Dengan nada tinggi, kalau satria sudah tersinggung, juga akan mengeluarkan murkanya.
Keempat, mental Sengkuni. Mental Sengkuni adalah gaya hidup orang Jawa yang serba licik. Nama yang se¬benarnya Sengkuni di dalam ki¬tab Mahabharata ada-lah Sakuni, kemudian dalam pedalangan berubah menjadi Seng¬kuni untuk memuda-hkan pengucapannya. Kitab Purwacarita menyebutnya Trigan¬talpati. Kitab Pustakaraja menamakan Suman. la adalah putra Prabu Keswara, juga dise¬but Prabu Swela, Pra¬bu Gandara yang ber¬kedudukan di kera¬jaan Gandaradesa (Harghana dan Aji, 2004:104). Sengkuni memang cerdas IQ-nya. Dia pintar mengolah kata. Bahasa polesan telah dia hafalkan. Bahasa racun dia balut menjadi madu, agar pihak ;lain terpikat. Kesuksesan yang dibangun, atas dasar kecerdikan. Dia seakan-akan menguasai psikologi massa. Maka gaya untuk kemenangan dirinya ditempuh dengan aneka rupa, yang seakan-akan sah. Karena watakmya yang jahat dan selalu mendambakan jabatan yang tinggi, maka Sengkuni setiap hari kerjanya hanya merangkai si¬asat untuk memfitnah dan menjatuhkan kedudukan orang lain. Suatu hari ia ingin membalas sakit hatinya ketika dikalahkan Pandu. Sengkuni kemudian memfitnah Pandu dengan melapor Prabu Trem¬boko raja Pringgondani yang sebenarnya masih siswanya Prabu Pandu. Putra-putra Tremboko antara lain Harimba, Brajadenta, Brajamusti, Brajamikaipa, dihasut. Mereka ditakut-takuti akan dibinasakan oleh Pandu. Sebaliknya kepada Pandu ia melapor bahwa putra-putra Pringgondani hendak menyerang Astina.
Dari kisah itu, apabila Antlov (2001:259) pernah mencatat hadirnya transisi demokrasi yang dibarengi krisis moral kepemimpinan, memang tidak salah. Gaya Sengkuni yang penuh muslihat jitu, telah menjawab, bahwa morkecilas rakyat Yogyakarta ternyata dapat ditukar gaya reformasi ironik ini. Yang saya maksudkan ironik, ketika reformasi menghendaki kepemimpinan bersih, jika figur yang akan berkecimpung dengan undang-undang telah “kotor moral”, bagaimana? Pada saat caleg mampu membaca tradisi dan agama sebagai kendaraan merengkuh kursi, yang nota bene materi yang bermain, kelak akan jadi apa negeri ini.
Sumantri dan Waluyo (1999:145-146) mempunyai simpulan bahwa Sengkuni itu tokoh yang licik, dengki, dan pengecut. Manuver politik yang dilontarkan Sengkuni selalu menjelekkan pihak Pandawa. Apa pun alasannya, gaya Sengkuni demikian ternyata banyak mewarnai Pemilu Legislatif. Orang Jawa bilang, ada watak tidak terpuji yang mirip Sengkuni yaitu drengki, srei, jail, methakil, mbedhidhil, dan uthil.
Begitulah gaya atau trik Sengkuni yang benar-benar penuh bisa. Kata Mulyono (1979:70) Sengkuni yang “klemak-klemek” dan penuh fitnah, emmang gambaran watak manusia penghasut. Dia tukang fitnah, yang mengolah suara tampak manis. Sesuai asal kata Sengkuni, dari Sakuni (saka, artinya asal) uni (ucapan). Jadi segala ucapan Sengkuni memang penuh tipu maut.
Yang perlu direnungkan, gaya Sengkuni memang julig. Hingga pernah terjadi Prabu Pandu yang menganggap bahwa tindakan Gandamana dianggap bersalah karena menghakimi Sengkuni tanpa sepengetahuannya. Karena itu se¬bagai hukumannya, Gandamana diusir dari Astina. Gandamana mene¬rima hukuman itu lalu kembali ke negara Pancala. Ketika Prabu Pandu mangkat dan tahta Astina dititipkan kepada Drestarata, Sengkuni mulai menghasut Kurawa agar menuntut secara resmi negara Astina. Dengan berbagai cara yang licik dan jahat Sengkuni berhasil menyingkirkan Pandawa dari Astina dan menampil¬kan Duryudana sebagai kandidat raja Astina. (Lakon Bale Segala¬gala). Setelah Duryudana resmi menjadi raja Astina, kejahatan Sengkuni kian menjadi jadi. la pernah berbuat tak senonoh dengan Dewi Kunti dengan meremas payudaranya, sehingga Kunti bersumpah tidak akan mengenakan semekan bila tidak dengan kulitnya Sengkuni. Berulang kali Sengkuni dan Kurawa berusaha melenyapkan Pandawa, namun mereka selalu gagal. Politik itu tidak mungkin steril dari berbagai pengaruh, seperti ihwal estetik, etik, dan kapitalistik. Pengaruh-pengaruh itu menandai bahwa budaya politik dari sisii antropologi sastra, senantiasa menggunakan gaya-gaya tradisi dan sastra untuk mencari kemenangan.
Dari catur gatra, artinya empat bentuk mentalitas Jawa tersebut patut mendapat perhatian khusus. Mengubah mental Jawa yang sudah mengakar sebagai akibat pengaruh budaya lain itu, perlu melibatkan strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan berisi haluan umum yang berperan memberi arah bagaimana kebudayaan akan ditangani, supaya tercapai kemaslahatan hidup berbangsa. Oleh karena kebudayaan juga menyangkut cara berpikir, merasa dan bertindak, ‘revolusi mental’ harus mengarah ke transformasi besar yang menyangkut corak cara-berpikir, cara-merasa dan cara bertindak.
Jadi, untuk agenda revolusi mental, kebudayaan mesti dipahami bukan sekadar sebagai seni pertunjukan, pameran, kesenian, tarian, lukisan, atau celoteh tentang moral dan kesadaran, melainkan sebagai corak/pola cara-berpikir, cara-merasa, dan cara-bertindak yang terungkap dalam tindakan, praktik dan kebiasaan kita sehari-hari. Agar revolusi mental menjadi siasat integral tranformasi kebudayaan, yang dibutuhkan adalah menaruh arti dan praksis kebudayaan ke dalam proses perubahan ragawi menyangkut praktik dan kebiasaan hidup sehari-hari pada lingkup dan skala sebesar bangsa. Revolusi mental, bangsa ini sangat membutuhkan taubat nasional, agar terbentuk mental-floss, artinya mentalitas Jawa yang lembut. Mental Jawa demikian berwajah jernih, penuh senyum.
Tegasnya, revolusi mental dalma budaya Jawa perlu mengubah mental tempe, yang konotasinya adalah sesuatu yang lembek, tidak keras dan mudah hancur. Mental yang demikian ini adalah mentalnya orang-orang yang tidak berani bersaing, kalah sebelum berperang, dan tidak bisa diharapkan sebagai pemimpin. Revolusi mental orang Jawa juga sedapat mungkin menjauhi mental manggis, yang gemar “mlothot”, artinya menekan orang lain, sementara yang menekan tertawa terbahak-bahak. Mungkin yang lebih manis, mengubah mental temped an mental manggis menjadi mental suruh, penuh kedamaian. Mari kita renungkan.
D. Penutup
Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati.
Pada penghujung pidato ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dari proses pengusulan, pemberkasan, sampai penetapan surat keputusan jabatan Guru Besar ini saya terima sehingga dapat berdiri di hadapan para hadirin yang budiman.
Pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Dirjen Dikti dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang telah mempercayai saya menduduki jabatan Guru Besar di bidang keilmuan Antropologi Sastra Jawa, sebuah ilmu baru yang unik dan menarik, namun belum banyak dilirik oleh banyak orang. Selanjutnya, ucapan terima kasih secara tulus saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Rohmat Wahab, M.Pd., MA, selaku rektor atas bimbingan, arahan, petuahnya dan Bapak ketua Senat Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum. serta Sekretaris Senat, Bapak Prof. Dr. Jumadi, yang telah memberikan dukungan dan bimbingan baik melalui tatap muka maupun SMS, dan seluruh anggota senat UNY sungguh telah menyetujui, memproses, mengusulkan, dan melancarkan upaya meraih jabatan ini.
Kedua, saya sampaikan penghargaan kepada Bapak Dekan FBS UNY, para Wakil Dekan FBS, Bapak Ketua Senat FBS dan anggota senat, tim pemberkas angka kredit, tim review karya ilmiah dan pengabdian internal yaitu Bapak Prof. Dr. Suminto A Sayuti dan Ibu Prof. Dr. Endang Nurhayati, M. Hum. Tim tujuh, yaitu Prof. Dr. Rohmat Wahab, M.Pd.,MA, Prof. Dr. Ahmad Dardiri, Prof. Dr. Jumadi, Prof. Suminto A Sayuti, Prof. Dr. Zamzani, M.Pd., Prof. Dr. Endang Nurhayati, dan Prof. Dr. Suwarna, yang telah dengan cermat meyetujui bidang keilmuan Antropologi Sastra Jawa. Tim penyerasi naskah pidato yang terdiri dari Bapak Prof. Dr. Rohmat Wahab, M.Pd.,MA, Prof. Dr. Ahmad Dardiri, Prof. Dr. Jumadi, Prof. Suminto A Sayuti, Drs Wardan Suyanto, MA, Ed.D, Prof. Dr. Endang Nurhayati, dan Prof. Dr. Suwarna, yang telah memberikan masukan dan koreksi demi kesempurnaan. Begitu pula kepada yang terhormat, para reviewer eksternal, Bapak Prof. Dr. PM. Laksono MA (UGM), Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA (Unhas), Prof. Dr. Marsono, SU. (UGM), dan Prof.Dr. Udjang Pairin, M.Pd. (Unesa), saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, saran, input, dan pencermatan terhadap karya-karya saya sehingga dapat diterima.
Ketiga, terima kasih secara khusus, juga saya sampaikan kepada dimas Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., raka Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., atas bantuan dan dukungan yang luar biasa, Bapak Prof. Dr. Zamzani, M. Pd., Prof. Dr. Suwarna, M.Pd. atas pertimbangan dan sumban saran yang amat berharga, Drs. Nasrudin B Tou, Ph.D., sahabat saya badminton yang telah mencairkan suasana tidak terduga, sehingga getaran dag-dig-dug saya menjadi tenang, Drs. Afendy Widayat, M.Phil, Dr. Mulyana, M.Hum, Dr. Purwadi, M. Hum yang telah penuh canda mendorong dengan “traktor ajaib” demi kelancaran usulan saya. Tidak ketinggalan Ibu Venny Indria E, M.Litt, Avi Meilawati, MA, Nur Hidayati, M. Hum., Sri Hertanti Wulan, M. Hum. yang telah dengan tulus ikut memberikan dukungan, khususnya persoalan apload data-data yang amat rumit dan pelik.
Keempat, kepada para guru saya selaku pembuka jalan hidup di SD Tegalsari Kulon Progo, khususnya wali kelas III Bapak Mujiman yang amat tegas dan wali kelas VI bapak Suwarjiono yang pernah mengajak saya ke rumah beliau, mandi di sungai, ketika saya dipercaya ikut lomba mengarang tingkat Kabupaten Kulon Progo. Guru SMP BOPKRI Samigaluh tempat saya menimba ilmu harus berjalan 5 km setiap hari dengan tanpa alas kaki (nyeker), utamanya kepada Bapak Samidjo ST, selaku Kepala Sekolah SMP tersebut yang banyak memberikan pencerahan batin, guru SPG BOPKRI Kota Yogyakarta, wajah rupa dan gaya mereka telah memberikan ajaran dan mendidik selalu terbayang, bapak Suhir guru bahasa Jawa SPG BOPKRI dan ibu Supartinah (guru BP) yang pernah nimbali saya ke kantor Beliau, dengan kaget ternyata gara-gara baju saya sobek, keduanya telah menginspirasi diri saya memasuki hutan rimbun (meminjam istilah Victor Turner dalam bukunya The Forest of Symbol), program studi Pendidikan Bahasa Jawa IKIP Yogyakarta, yang penuh dengan semak-semak. Dosen-dosen saya di jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FPBS IKIP Yogyakarta, terutama almarhum Bapak Drs. Sarjana HA dan Drs. Mukidi Adisumarto, yang telah mendorong saya mendaftarkan diri menjadi dosen waktu itu, saya ditelepon ke Harian Kedaulatan Rakyat, tempat saya bekerja sebagai redaksi Mekar Sari, yang diterima oleh Pemred Bapak Suwariyun (almarhum), sehingga saya ditanting, akan menjadi dosen atau tetap sebagai redaktur. Terima kasih yang tiada batas kepada beliau, juga Rama Ndung (Handung Kus Sudyarsana, almarhum) dan mas Bondan Nusantara di redaksi Mekar Sari, yang telah mengajari bermain ketoprak, menulis berita, dan lek-lekan makan gudeg di depan KR.
Kelima, demikian juga kepada Bapak Drs. Asia Padmopuspito (almarhum) yang dengan gaya “nggih” ketika membimbing skripsi bersama bapak Drs. RS. Subalidinata (UGM) sebagai pembimbing 2, yang mengizinkan saya ikut kuliah di Fakultas Sastra UGM dan di rumah beliau kuliah sambil nyruput teh, sungguh sulit saya lupakan. Kepada Bapak Prof. Dr. Suhardi, MA. pembimbing tesis S2 di FIB UGM, yang amat saya hafal mobilnya setiap mau konsultasi harus mengintip di bawah pohon, telah mengarahkan diri saya mempelajari mistik kejawen, beliau sekaligus ko-promotor bersama Bapak Prof. Dr. PM. Laksono, MA, masih melanjutkan pendalaman mistik kejawen dalam kehidupan penghayat, telah memberikan gemburan-gempuran akademik bersama promotor saya Bapak Prof. Dr. Kodiran, MA, yang amat tulus, sabar, dan jeli mencermati disertasi hingga mampu meraih gelar doktor di bidang Mistik Kejawen. Sungguh beliau bertiga telah memberikan keleluasaan menulis etnografi dalam disertasi menggunakan kata “saya”, sehingga saya tulis seperti halnya sebuah novel ilmiah.
Keenam, tidak lupa pula kepada rekan seangkatan saya Drs. Suman (almarhum), Drs. Suprayitno, Drs. Heru Kimpul, Drs. Y Siyamto, yang sering berdiskusi dan bersama jajan bakwan sebagai lauk nasi rames di Karangmalang dan Samirono. Begitu juga kepada teman-teman Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta, ibu Dra. Sri Widati Pradopo, Drs. Pardi Suratno, M. Hum. Sekarang Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Drs. Dhanu Priyo Prabowo, M. Hum., Drs. Sri Haryatmo, Drs. Tirto Suwondo, M. Hum. Sekarang Kepala Balai Bahasa Yogyakarta, Drs. Hery Mardiyanto, Dra, Prapti Rahayu, Drs. Imam Budi Utama, M. Hum. sekarang Kepala Bahasa Kaltim, Drs. Y Adhi Satyaka, sekarang menjabat ketua SSJY, atas suntikan-suntikan imajinasi, saya bisa menulis geguritan, cerita pendek, cerita sambung, dan lain-lain. Terima kasih yang dalam kepada ketua HISKI Komda DIY, terutama kepada ketuanya Prof. Dr. Suminto A Sayuti telah diganti mas Drs. B. Rahmanto, M. Hum. dan sekarang dijabat mas Drs, Jabrohim, MM, dosen UAD, yang telah bersama saya berolah sastra. Tidak ketinggalan teman-teman pengurus Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, ibu Dr. Pudentia, MPSS, dosen UI, yang telah mempercaya kami di DIY mendirikan ATL Komda DIY, yang pengurusnya semi aktif yaitu kanda Prof. Dr. Kasidi Hadiprayitno (ISI), Dr. Pujiharto, M. Hum. (UGM), Dr. Yosep Yapi Taum, M. Hum. (USD), Drs. Afendy Widayat, M. Phil. (UNY), Drs. Dhanu Priyo Prabowo, M. Hum. (Balai Bahasa), Dr. Dian Kuardani, M. Hum. (ISI), Drs. Nur Iswantoro, M. Hum. (ISI), atas bantuan pemikiran dan upayanya menggairahkan tradisi lisan, sastra lisan, dan budaya lisan.
Ketujuh, akan tidak lengkap apabila tidak saya sebutkan, yaitu organisasi dan instansi yang sering bekerjasama dan mengundang saya untuk saling bertegur sapa untuk memajukan sastra, seni, dan budaya khususnya di DIY, antara lain kepada Bapak Kepala Dinas Dikpora, mas Drs. Baskara Aji K, MM, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Drs. GBPH Yudaningrat, MM, sahabat kental saya raka Prof. Dr. Setya Yuwana Sudikan, MA, Dekan FBS UNESA, yang selalu memotivasi dari jauh, bapak Kepala BTKP, Kepala BPKB Sorowajan, Dirjen Kebudayaan dan Direktur Kepercayaan Jakarta, Kepala Pusat Studi Asia Pasifik UGM, Kepala JTTC UGM, Rektor IHDN Denpasar Prof. Dr. I Nengah Duija, M. Hum., seluruh Ketua Jurusan/kaprodi bahasa daerah UGM, UPI, Unesa, UI, Uness, Univet, UNS, UMP, Universitas PGRI Semarang, Undheksa Singaraja, Unhas, Unlam, kakaprabu Joko Budhiarto Redpel KR, Pepadi, dan Sangsisaku, rekan Dewan Perpustakaan DIY, Kepala BPAD, Kepala Museum Sonobudoyo, Kepala BPNB mbak Otik atau Dra. Christriyati Ariani, M.Hum., Yayasan Gambir Sawit tempat saya belajar kendang dan gender, Rekan Masyarakat Tradisi Bantul (MTB), pengurus IKADBUDI (Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia), pengurus KESAWA (Keluarga Alumni Basa Jawa), Redaksi Djaka Lodang, Redaksi Harian Kedaulatan Rakyat terutama pada mas Drs. Octo Lampito, M.Pd. Pemred KR dan mas Drs. Jayadi K Kastari pemegang rubrik sastra dan budaya, Harian Suara Merdeka, terutama pada mas Triyanto Triwikromo, Jogja TV kepada mas Andhi Wisnu W, TVRI Yogyakarta kepada mbak Nur Iriyanti dengan rubrik Cangkriman, mbak Iwung Widati dengan rubrik Karangtumaritis, ketua MGMP Bahasa Jawa SMP, SMA, SMK, KKG SD, redaksi majalah berbahasa Jawa Sempulur Dinas Kebudayaan DIY, Mas Sutopo Ketua Lembaga Budaya Jawa Kinanti, mas Danuri dari Lembaga Budaya Jawa (Lembujawa), Direktur Penerbit Media Presindo Group mas Indra Ismawan, SE, Direktur penerbit Gadjah Mada University Press, Direktur Penerbit UNY Press, Direktur Penerbit Ombak, Direktur penerbit Wedatama Widya Sastra Jakarta, Direktur penerbit Kuntul Press dan Buana Pustaka, seluruhnya telah ikut menopang dan mengorbitkan saya dalam berbagai kegiatan sastra, seni, dan budaya.
Kedelapan, rekan-rekan sastrawan, seniman, dan budayawan seperjuangan, teristimewa konjuk Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwana X, pengayom seniman-budayawan, yang telah maringi kekancingan saya sebagai pelestari budaya Jawa tahun 2009, Bapak Ajib Rosidi yang member hadiah sastra Rancage tahun 2006, RPA. Suryanto Sastroatmodjo (almarhum), Ir. Yuwana Sri Suwito, MM, mas AY Suharyono, Kang Minto, mas Warsito, Ki Rejomulyo, mas Sukisno, mas Indro Tranggono, Sigit Sugito, Ons Untoro, Agus Leylor, Titik Renggani, Angger Sukisno, Yati Pesek, Turiyo Ragilputro, Dwianto B Utomo, Tatik Kalingga, Sucipto Hadi Purnomo, Imam Budhi Santosa, Umi Kulsum, Dalijo Angkringan, Yati Pesek, Krishna Miharja, MG Widhy Pratiwi, Sareh Atmojo, Rama Projosuwasono, Djaimin K, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, telah bersama-sama saya mendukung dan membesarkan DIY.
Hadirin yang terhormat.
Pada kesempatan emas ini, saya harus menundukkan kepala, sepenuh hati, atas kasih sayang orang tua yang masih dikaruniai kesehatan, Bapak Sumarji yang bekerja keras di “Departemen Pertanian”, telah adus kringet mencangkul di tegal dan sawah mencari uang kuliah dan sering mencari dana talangan ke tetangga dan saudara. Ibu Suminah yang menekuni kerja di “Departemen Perdagangan”, sebagai bakul eber-eber, yang berjiwa tuna satak bathi sanak, sehingga selalu tulus mbanyu mili, telah melahirkan mata air suci dari pegunungan Menoreh Kulon Progo dengan ketulusannya selalu menyiram dan menembus hati sanubari hingga tinarbuka ketika saya harus menghadapi keadaan dunia yang semakin jempalitan. Keduanya pernah sakit boyok dan stress berat, saya hanya dapat berdoa semoga diberi ketabahan, kesabaran, dan kesehatan. Begitu pula Pak Lik saya Gatut Susanta dan Bu Lik Supartinah, yang dengan sabar mengarahkan kuliah saya, memberi motivasi, dan “menjewer telinga” saya apabila bermalas-malasan, dan menyediakan kost gratis di balik dinding bambu, yang waktu itu sekaligus sebagai kandang ayam, ternyata sering menggugah tidur saya dengan berkokok keras. Sungkem kepada Bapak dan ibu mertua (almarhum) yang seharusnya akan naik haji bersama saya tahun 2012, ternyata Allah terburu memanggil beliau. Mereka telah merelakan bidadarinya bergabung dalam suka duka menjalani ritme kehidupan ini. Kasih sayang beliau ketika saya sakit hampir 1,5 tahun, setiap pagi selalu menyediakan bubur pagi, siang, dan sore sulit saya lupakan.
Maaf, jika yang satu ini terabaikan, maka bisa “meruntuhkan keselamatan keluarga saya”. Adalah istriku Dra. Hj. As Sartini yang pertama kali bertemu di parkiran FPBS Barat, dengan mengendarai Honda 70, kalau menggenjot lebih 10 kali, gara-gara genjotan itulah saya semakin dekat penuh kasih sayang, hingga melahirkan anak secara gilir kacang, yaitu Hilmy Pramusinta, telah lulus di PJKR FIK UNY, Lutfy Laksita Pranandari, masih kuliah di Undip, Faqih Zakky Anindita, sekolah di bidang olah raga SMA 1 Sewon, dan adiknya Hafiz Afifah Nawangsari di SMA 1 Bantul. Saya mengakui tanpa dorongan isteri, yang tekun dan cermat terlebih sebagai “pembaca sms saya”, sering mengingatkan harus menuju jalan lurus, penuh pengertian berebut cop-copan listrik, dan menghadiahi salam dan cium ketika saya mendapatkan kenikmatan apa saja.
Akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang dengan sabar telah mengikuti pidato pengukuhan saya. Mohon maaf segala khilaf, ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita. Akan saya tutup pidato dengan sebuah tembang Pangkur.
paripurna atur kula
para mitra paring pangaksami
mugi Gusti maha agung
ambabar jatining rat
wus amatur paduka sagung tamu
mugi tansah lestaria
sartane manggih basuki
Wal'afu minkum
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Daftar Pustaka
Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2003. “Dari Antropologi Budaya ke Sastra, dan Sebaliknya” dalam Muh Arif Rokhman Dkk. (Ed.) Sastra Interdisipliner; Menyandingkan Sastra dan Disiplin Ilmu Sosial. Yogyakarta: Qalam.
_____________________. 2004. Strukturalisme Levi-Strauss; Mitos dan Karya Sastra. Yogyakarta: Galang Press.
Antlov, Hans. 2001. “Elit Desan dan Orde Baru” dalam Kepemimpinan Jawa. Jakarta: yayasan Obor Indonesia.
Arintoko. 1984. Gending Dolanan. Yogyakarta: P dan K Kepatihan.
Benson, Paul. 1993. Anthropology and Literature. Chicago: University of Illinois Press.
Endraswara, Suwardi. 2010. “Orang Jawa Memandang Perang Kembang”, Makalah: Seminar Nasional Gugur Gunung Kamasutra FIB Universitas Gadjah Mada, 11 Desember.
__________________. 2011. “Karakter Berpikir Positif Melawan Korupsi Dalam Sastra Lisan Dan Terobosan Inovatif Pembelajaran Bahasa Jawa di SLTA DIY, Jateng, Dan Jatim: Dengan Catatan Tebal. Makalah Kongres Bahasa Jawa 5 di Surabaya, 25-30 November.
_________________. 2012. “Psikologi Jawa: Kramadangsa dan Anomali Watak Bangsa”. Jakarta: Makalah Junggringan Ki Ageng Suryamentaram, Jl. Barito Jakarta, 13 Januari.
__________________. 2013. Metodologi Penelitian Antropologi Sastra. Yogyakarta: Ombak.
Geertz, Clifford. 2000. Negara Teater; Kerajaan-Kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas. Yogyakarta: Bentang.
Harghana, Bondhan dan Moh. Pamungkas PBA. (2001). Bunga Rampai Wayang Purwa Beserta Penjelasannya. Jilid 2. Sukoharjo: CV Cenderawasih.
Hutomo, Suripan Sadi. 1984. Antologi Puisi Jawa Modern. Jakarta: Pustaka Jaya.
___________________. Angin Sumilir; Antologi Geguritan. Jakarta: Balai Pustaka.
Jokowi, “Revolusi Mental.” Jakarta: Kompas, hal. 6, Sabtu, 10/5/2014. Keesing, Roger. 1992. Antropologi Budaya; Suatu Perspektif Kontemporer. Jakarta: Erlangga.
Keesing, Roger. 1992. Antropologi Budaya; Suatu Perspektif Kontemporer. Jakarta: Erlangga.
Mulyono, Sri. 1979. Wayang dan Karakter Manusia. Jakarta: Gunung Agung.
Palmer, Richard E. 2005. Hermeneutika; Teori Baru Mengenal Interpretasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pete, Jayus. 2001. “Petruk” Cerpen Jawa. Surabaya: Yayasan Pinang Sirih dan DKS.
Ragilputro, Turiyo. 1990. “Srengenge”, Cerpen Jawa. Surabaya: Panjebar Semangat, nomor 12, 17 Maret, termuat dalam Niskala; Antologi Cerpen Eksperimen.
Ratna, Nyoman Kutha. 2011. Antropologi Sastra; Peranan Unsur-unsur Kebudayaan dalam Proses Kreatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saprodjo, Gito. 2002. Primbon Cakepan Tembang Lengkap. Sukoharjo: CV Cenderawasih.
Senggono. 1991. ”Semilyar” Crita Cekak. Surabaya: Jaya Baya.
Subagyo. 1992. Parikan Jawa Puisi Abadi. Jakarta: PT Aksara Garda Pustakatama.
Supadjar, Damardjati. 2001. Mawas Diri. Yogyakarta: Philosopy Press.
Suryamentaram, Ki Ageng. Kawruh Jiwa jilid 3, Jakarta: CV Haji Masagung.
Tedjohadisumarto.1958. Mbombong Manah. Jakarta: Djambatan.
Toelken, Barre. 1979. The Dynamics of Folklore. London: Dallas Geneva, Illinois Hopewell, New Jersey Palo Alto.
Wacik, Jero. 2010. Berpikir Positif Modal Hidup Saya. Jakarta: Ekslusif Publishing.
Wellek, Rene dan Austin Warren. 1989. Teori Kesuasteraan. Terjemahan. Melani Budianto. Jakarta: Gramedia.
Widodo, Sri. 1995. Gending-Gending Dolanan. Sukoharjo: CV Cenderawasih.
Address: Colombo Street No 1, Yogyakarta 55281,
Phone (0274) 550843, (0274) 546719, Fax (0274) 548207
Website: http://fbsb.uny.ac.id
Email: fbsb@uny.ac.id;
Copyright © 2025,